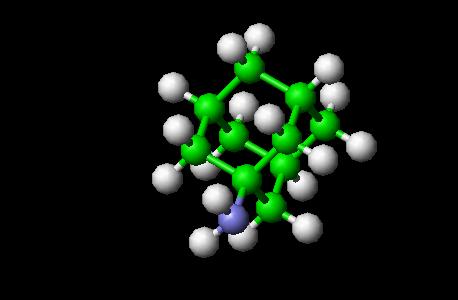(ditulis sekitar 1 tahun lalu, esensi isi masih relevan, terkait dengan makin maraknya obat herbal di pasaran).
(ditulis sekitar 1 tahun lalu, esensi isi masih relevan, terkait dengan makin maraknya obat herbal di pasaran).Akhir-akhir ini fenomena si buah merah sangat menarik, seperti banyak diberitakan di media massa, termasuk harian ini. Khasiat buah yang sudah dikonsumsi turun temurun di Papua ini diklaim mampu menyembuhkan berbagai penyakit seperti kanker rahim, paru-paru dan lever. Juga ampuh bagi para penderita diabetes, hipertensi, prostat, asam urat, stroke maupun wasir. Bahkah belakangan sudah dilaporkan sudah memberi hasil baik pada penderita HIV/AIDS. Khasiat tersebut, menurut penemunya Dr. I Made Budi, MSi, karena buah merah diantaranya banyak mengandung betakaroten, tokoferol dan asam lemak seperti asam oleat, linoleat, linolenat dan dekanoat disamping berbagai vitamin dan mineral seperti kalsium dan Fe (zat besi). Begitu menjanjikan memang, bagaimana mensikapinya ?
Laporan WHO mencatat sekitar 80% masyarakat di negara sedang berkembang mengandalkan obat tradisional untuk pelayanan kesehatan dasar akibat kurangnya pengetahuan atau faktor tradisi. Sementara di negara-negara maju, para pasien memilih obat herbal karena keyakinan akan sifat alamiah yang aman. Sayangnya, ini diikuti juga oleh meningkatnya laporan reaksi merugikan (adverse reaction). Selama tahun 2002, diperoleh laporan adverse reaction sebanyak 9.854 kasus di China dimana terapi tradisional banyak digunakan bersama terapi konvensional (WHO, 2004).
Berdasarkan tingkat keamanannya, guidelines dari WHO membagi obat herbal menjadi 4 kategori. Pertama adalah indigenous herbal medicine, yang secara historis turun temurun banyak dipakai pada kalangan lokal atau daerah tertentu. Dokumen rinciannya kadang ada, tetapi biasanya sulit didapatkan, dan boleh digunakan secara lokal.
Kedua, herbal medicine in system, dimana obat sudah dipakai secara turun temurun dan tersedia dokumen tentang teori dan konsep yang mendasarinya, sehingga bisa diterima oleh banyak negara. Contohnya ; Ayurveda, Unani dan Siddha.
Selanjutnya, bisa dilakukan modifikasi terhadap obat herbal agar memenuhi standar keamanan dan efikasi (modified herbal medicines). Persyaratan akan lebih ketat bila sudah memasuki pasaran ekspor (imported products with a herbal medicine base).
Di Indonesia, Badan POM mengarahkan pengembangan obat tradisional menjadi tiga kelompok berjenjang, yaitu jamu sebagai warisan budaya. Setelah menjalani uji farmakalogi dan baku terstandarisasi, disebut sediaan herban berstandar. Sedang kategori fitofarmaka mengharuskan uji klinik pada manusia. Sayangnya, proses uji klinik ini tidak mudah. Sementara klaim soal efektifitas obat herbal sudah terlanjur banyak kita dengar.
WHO sendiri menetapkan protokol ketat untuk baku mutu melalui Good Agricultural and Collection Practices (GACP) dan Good Laboratory Practices (GLP) untuk mengawal baku mutu sejak dari bahan mentahnya. Kekhawatiran tidak adanya baku mutu ini juga dilontarkan oleh penemu obat merah, meski sudah mengantongi nomor register dari Depkes, karena bamyak pihak mengklaim sebagai produsennya, tanpa standar produksi yang jelas dari pihak berwenang.
Sementara itu, buah merah hanya salah satu dari sekian banyak produk yang diklaim memiliki efek terapi untuk penyakit-penyakit medis, sehingga muncul dorongan agar bisa dimasukkan dalam resep dokter. Fenomena maraknya obat herbal (fitofarmaka) ini sering membuat para dokter kikuk bila harus menjawab pertanyaan dari pasien. Bisa dipahami, bila mereka yang berpegang pada konsep evidence-based medicine tidak mudah menerima hadirnya klaim-klaim semacam itu.
Sekedar contoh, anti-oksidan pada buah merah diklaim bersifat anti-kanker, disamping adanya tokoferol (salah satu anti-oksidan) yang mencegah penyakit jantung kooner. Sementara, meskipun secara teoritis klaim tersebut beralasan, review terhadap laporan penelitian terapi dengan anti-oksidan belum mampu memastikan keguanan vitamin seperti A, C, E atau Beta-carotene dalam mencegah penyakit kardiovaskuler, bahkan pada sebagian laporan berefek negatif. Alasannya, hasil-hasil penelitian masih kontradiktif, dan sebagian besar merupakan studi epidemiologis yang didasari bukan oleh pemeriksaan klinis, namun data historis dan laporan susunan diet subyek penelitian (Hasnain & Mooradian, 2004).
Apalagi, ada juga laporan-laporan efek tidak diinginkan dari penggunaan dan overdosis anti-oksidan. Asupan vitamin C dosis tinggi misalnya bisa mengarah ke gangguan saluran cerna (diare) sampai gangguan perdarahan pada penderita defisiensi G6PD, atau aritmia pada orang yang kelebihan zat besi. Overdosis vitamin A bisa memicu osteoporosis dan teratogenisitas, sementara vitamin E bisa memperburuk retinitis pigmentosa serta risiko stroke hemorrhagis. Ada juga laporan kegagalan operasi oleh perdarahan, yang setelah ditelusuri akibat konsumsi jangka panjang Ginko biloba.
Para pasien, cenderung tidak terbuka terhadap dokter bila dirinya – secara terpisah atau bersama-sama obat medis – juga mengkonsumsi obat herbal. Uniknya, bila akhirnya sembuh, cenderung “keberhasilan” tersebut dialamatkan pada obat herbal. Sementara saat ternyata gagal, cenderung dokter/obat medis yang dituding tidak mampu mengobati, bahkan bisa dituding menjadi penyebab kematian pasien. Padahal laporan WHO menyebut, salah satu penyebab adverse reaction adalah tidak dilaporkannya penggunaan obat herbal kepada dokter yang merawat, termasuk kasus perdarahan saat operasi pada contoh sebelumnya.
Lontaran yang sama muncul dari ahli AIDS FKUI yang menyatakan, banyak penderita HIV/AIDS berhenti berobat beralih ke buah merah, padahal obat bagi mereka saat ini masih gratis. Dokter tidak mengetahui, tetapi mendapat laporan dari para pendamping. Akibatnya sejumlah pasien sampai meninggal. Sementara, menurut dokter tersebut, penderita yang membaik dengan buah merah sebenarnya adalah yang masih tetap bersama-sama menggunakan obat dari medis, artinya karena obat anti virusnya.
Intinya, sering terjadi kebuntuan komunikasi antara dokter-pasien dalam hal terapi alternatif. Kondisi ini diperparah oleh suasana yang seolah secara diametrikal menempatkan dokter dengan “terapi konvensional” di satu sisi dengan “terapi alternatif” di sisi lain, termasuk – atau terutama – obat herbal. Uniknya, para praktisi terapi alternatif tidak jarang mendasarkan klaim efektiftas obat herbal dengan perbandingan terhadap “terapi konvensional”, tanpa melalui suatu uji klinik standar.
Bila berpegang pada prinsip evidence-based medicine tentu saja dokter tidak bisa menerima suatu obat herbal tanpa penelitian yang standar. Namun, data-data empirik pada hampir semua klaim obat herbal, seperti misalnya yang dipaparkan oleh penemu buah merah, tentu tidak bisa begitu saja diabaikan. Sementara ke depan, WHO sendiri mengharapkan obat tradisional bisa dikembangkan secara ilmiah, agar nantinya peresepan harus oleh tenaga berkualifikasi, guna meminimalkan adverse reaction.
Disisi lain, pertumbuhan industri dalam hal obat herbal juga makin marak, sehingga secara ekonomis akan memiliki dampak bagi penghasilan mereka yang terkait di dalamnya, termasuk para petani di lapisan bawah yang mulai melirik harapan menanam bahan mentah obat herbal.
Menghadapi kenyataan ini, mau tidak mau, jalan tengah harus dicari. Secara manusiawi, tidak ada penggunaan obat herbal yang bertujuan buruk, sayangnya juga tidak banyak yang sudah dilengkapi dokumen pendukung soal efektifitas dan keamanannya. Beberapa penelitian mendapatkan petunjuk akan manfaat kandungan zat dalam tanaman. Sebut saja seperti xeronine dalam mangkudu, organosulfur dalam sayuran jenis allium (seperti bawang putih), lycophene dalam tomat atau flavonoids dalam teh hijau, terbukti ada manfaatnya. Masalahnya, efek itu masih bersifat “multi-faces” untuk berbagai ragam penyakit, tidak spesifik. Karena itu yang bisa disepakati sejauh ini, meski ada beberapa yang bersifat short-action, efektifitas obat herbal lebih bersifat maintenance, jangka panjang, dan regeneratif.
Untuk itu, penulis berpendapat, penggunaan obat herbal sebaiknya mengikuti pola 5-R yaitu rapid-clearance, rythmic, re-check, relaps, dan report. Istilah ini rekaan penulis untuk mudah diingat.
Lebih jelasnya, kita ambil contoh konsumsi buah merah pada penderita diabetes. Langkah pertama kadar gula darah harus tetap dikendalikan lebih dulu dengan obat-obat medis (rapid-clearance). Setelah tercapai kadar terkendali, secara bersama-sama dengan obat medis mulai meminum "ramuan sehat" tersebut. Cara minum ini menuntut keteraturan/ketelatenan (rhytmic), bila tidak maka sulit dipastikan tercapai hasil maksimal (bila memang nantinya efektifitasnya terbukti). Pastikan pula, keputusan minum obat ini didiskusikan dengan dokter yang merawat.
Kemudian, check and re-check secara berkala tetap harus dijalankan, untuk melihat perubahan, termasuk untuk menyesuaikan dosis obat medis bila terjadi perbaikan atau perburukan. Yang tidak diharapkan, karena merasa kadar gula darah puasa dan 2 jam PP sudah terjaga, lantas berhenti check, yang penting terus minum obat herbal. Risiko hipoglikemia tidak lebih ringan risikonya daripada hiperglikemia pada penderita diabetes, bila tanpa pengecekan berkala. Paling tidak setiap 3 bulan ada baiknya re-check dengan HbA1c.
Di tengah kebiasaan rutin mengkonsumsi ramuan sehat ini tetap harus diwaspadai munculnya tanda-tanda perburukan (relaps). Misalnya penderita merasa jadi lebih sering mengantuk menjelang siang hari. Bila ini terjadi, jangan lantas sekedar merubah pola minum (misalnya ditambah sering), lebih baik diskusikan lagi dengan dokter agar diketahui mengapa sebabnya atau apa yang sebenarnya terjadi.
Terakhir, sangat baik bila mau melakukan pencatatan (report) perubahan-perubahan yang dirasakan dikaitkan dengan kebiasaan minum tersebut. Dari catatan tersebut, suatu saat akan mudah dilihat kapan ternyata muncul efek yang diharapkan maupun efek samping yang tidak diinginkan, bagaimana efek dari perubahan frekuensi dan takaran, dan seterusnya. Kalau ternyata berhasil baik, catatan yang rapi ini sangat baik. Kalaupun belum mendapatkan hasil yang diharapkan, catatan tersebut tetap berguna untuk dikaji kembali. Langkah reporting ini juga direkomendasikan oleh WHO agar tersusun dokumentasi obat herbal, guna kepentingan penelitian lebih lanjut, sehingga ada harapan akhirnya obat herbal bisa diterima dalam formula terapi medis, setelah melewati uji klinis paripurna.
Pola seperti ini, dalam hemat saya, akan bisa diterima oleh dokter, tanpa harus merasa “dikelabui” oleh pasien. Sekaligus dokter, pasien maupun pihak lain yang berwenang bisa mendapatkan pengalaman dan data baru, tanpa harus mengurangi saling percaya dalam suasana hubungan dokter-pasien. Ini tidak lantas berarti Badan POM dan yang terkait sekedar menunggu, tetap saja harus ada langkah proaktif sebelum akhirnya beban masalah yang mungkin timbul dalam soal tanaman herbal ini makin menggunung.